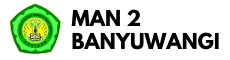Sering sekali mendengar nasihat, “ngono yo ngono, neng ojo ngono” dari kakek dan nenek kita. Falsafah hidup orang Jawa zaman dulu memang sangat mantab. Bentuk sindiran dalam bahasa Jawa itu memiliki makna yang sangat dalam. Sindiran yang merupakan nasihat itu sering aku dengarkan saat tingkahku mulai di luar batas. Ya namanya anak yang hidup di lingkungan kampung, dengan wahana permainan yang sangat alami, mulai dari manjat pohon, berenang di sungai, lari-lari di persawahan mengejar layangan putus, delikan atau jumpritan, sampai iseng-iseng mancing tapi kolamnya orang. Bocah ndablek kalau masyarakat menyebutnya. Maka jika polahe sudah keblabasen, maka kata-kata sindiran itu keluar. Seperti ada mantra magisnya. Tatkala mendengar sindiran syahdu itu dilontarkan, sekejap itu pula langsung memberhentikan polah-polah tak jelasku.
Kayaknya memang adatnya orang Jawa dalam hal pitutur sangat efektif. Jika dibanding zaman sekarang yang redaksi nasehatnya sangat panjang lebar, mulek, mbuh intine opo. Tapi zaman dulu yang ditradisikan oleh para sesepuh seperti orang tua kita, kakek-nenek kita hingga buyut-buyut kita memang nasehatnya sangat syarat dengan makna-makna filosofis. Pendek-pendek namun sangat mengena. Itu mungkin dikarenakan mereka banyak menyampaikan pendidikan melalui keteladanan. Mereka tidak akan memerintah anaknya untuk sholat berjama’ah jika mereka sendiri belum atau tidak melaksanakannya. Sehingga pantangan untuk menasehatkan A, jika dirinya belum benar-benar bisa A.
Kakek-nenek, orang tuaku sangat memahami bagaimana keaktifan anak-anak yang belum matang fungsi fikiran dalam hal pertimbangannya. Sehingga memaklumi bagaimana “kenakalan” anak-anak desa yang sangat terbatas wahana permainannya. Sehingga makna “ngono yo ngono neng ojo ngono” itu merupakan bentuk pemakluman atas kesalahan dan kecerobohan yang dilakukan anak, namun tetap harus mengontrol diri jangan sampai melampaui batasnya hingga merugikan orang lain. Bentuk motivasi juga untuk diri kita agar mengoptimalkan fungsi kontrol dalam diri agar tidak melewati batas-batas yang ditentukan mulai dari moral budaya, pendidikan, agama dan lain-lain.
Maka sesepele apapun kelakuan dan polah kita, kata kuncinya adalah “jangan sampai merugikan, menyakiti dan mengganggu orang lain”. Kalau didalami dan dikupas dari kata per-kata maka makna “ngono yo ngono” adalah pemberian ruang kebebasan untuk bersikap, berperilaku dan berekspresi. Namun sak ngono-ngonone, neng ojo ngono. Jadi sebebas-bebasnya dikasih ruang untuk berekspresi tetap moral sosial-budaya memaksa untuk membatasi polahmu. Karena secara sosial-budaya kita hidup berdampingan dengan manusia-manusia lain yang memiliki pola fikir, sensitifitas, kondisi perasaan, latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga konsekuensi logisnya adalah bagaimana tetap bisa harmoni, selaras dan sebisa mungkin menghindari gesekan, benturan dan konflik antar sesama manusia.
Dimulyakanlah oleh Allah nenek moyang orang Jawa yang mengajari anak cucunya suatu pedoman hidup yang sederhana bunyinya namun mencakrawala maknanya. Apalagi ketika disambungkan dengan keadaan wabah atau pandemi sekarang ini, yang semua orang bertarung melawan ketakutan, kekhawatiran dan keraguannya masing-masing atas kehidupannya. Ada yang mendekat dengan Tuhan, ada yang masih bertahan dengan kelalaiannya, ada yang tetap saja sombong, ada yang bingung dan menunggu nasib saja. Coronavirus memang kenyataannya adalah masalah medis-kesehatan. Namun juga tidak menutup kemungkinan lebih luas dari pada itu. Mungkin ia juga masalah logika, cara dan keputusan berfikir. Menguji bagaimana dunia keilmuan dan pengetahuan manusia dalam menghadapi masalah seserius ini. Ada kemungkinan juga masalah silaturrahmi vertikal, ranah spiritual-religius. Bisa saja masalah aqidah dan akhlak. Terserah manusianya mau memilih bidang penghayatan yang mana atas masalah ini.
Setiap orang, setiap keluarga, setiap lembaga, setiap perkumpulan manusia apapun seenggaknya berfikir ulang dan kembali kepada pedoman “ngono yo ngono, neng ojo ngono”. Benar yang benar, namun jangan merasa paling benar. Yakin ya yakin, namun jangan terlalu yakin, mungkin pada taraf dan situasi tertentu kita butuh ragu-ragu, dalam artian kehati-hatian, sehingga tidak sembrono. Memang benar sih ragu-ragu tidak baik, namun dalam ruang, kondisi dan perihal yang mengharuskan untuk ragu-ragu demi mendapatkan level kehati-hatian yang pas, lebih tepat mengambil itu. Karena keyakinan yang over-dosis bisa mengarah kepada kesembrononan, dalam masalah dan kasus wabah ini, dan kasus-kasus lain yang serupa. Sehingga jangan merasa paling sok yakin, sok berpasrah, sok paling dekat dengan Tuhan, sehingga keluar rumah sama sekali tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga menjurus pada hal yang berpotensi merugikan orang lain. Maka segala sesuatu harus empan papan. Keyakinan yang mantab seratus persen harus diempankan, ditempatkan, diterapkan dalam papan, kondisi, situasi, dimensi, ruang yang pas.
Betapa kerdilnya manusia dan betapa terbatasnya ilmu pengetahuan manusia mengenai nasib, taqdir dan masa depan, maka ada opsi sumber keselamatannya adalah memantabkan rasa rendah hati dan tahu diri di hadapan Tuhan. Itu pun tidak bisa dipastikan jika ia sudah rendah hati, dan taat kepada Tuhannya, bisa jadi ia dibuat meninggal oleh Tuhan karena corona, dengan tujuan menyelamatkan ia dari kemungkinan semakin banyaknya perihal dosa yang menghampirinya. Kalaupun kita tidak diselamatkan oleh Tuhan dari corona di dunia, semoga Tuhan menyelamatkan kita di akhirat. Wallahu A’lam Bish Showwab.
Oleh : Agus Novel Mukholis ( Guru MAN 2 Banyuwangi )
Tulisan ini sudah di muat/ di terbitkan di Radar Banyuwangi