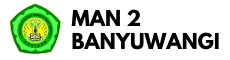Hati ini bergetar hingga getarannya dirasakan oleh semua bagian dari tubuh ringkih ini. Seakan setiap sel dalam tubuh berteriak mengekspresikan kekagumannya. Suara gemuruh apa itu. Hampir mirip dengan tangisan yang menggema bersama menjadi satu. Iya benar, ribuan kanak-kanak menjerit dengan tangisan melengking memanggil-manggil asma kekasih Sang Pemilik Jagad. Acara mujahadah saat itu memang didominasi oleh kanak-kanak seusiaku bahkan di bawahku. Nizam namaku dan ternyata sudah selama 12 tahun aku menghirup udara segar di bumi penuh teka-teki ini. Aku tinggal di sebuah desa di Kota rawa-rawa yang dulu ada pabrik gula tua telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Sehingga saking angkernya hingga tidak ada yang berani untuk sekedar melewatinya.
Seorang lelaki penuh wibawa dengan wajah teduh dan aura kedamaian menyelimuti dirinya, berdiri di podium acara mujahadah itu. Ya lelaki dengan usia 65 tahun itu adalah kakekku. Beliau bersama nenek adalah satu-satunya keluarga yang berani menempati rumah di dekat pabrik gula tua itu. Menyulap tempat itu menjadi tempat mengaji hingga sekarang menjadi hunian yang layak, terdapat masjid dan madrasah. Juga walaupun paling banyak 5 orang yang nyantri kepada Mbah Kakung. Namun bukan mengenai ilmu alat dan ilmu syari’at yang lain yang umumnya dipelajari di pesantren. Beberapa orang yang nyantri ke beliau ingin belajar mengenai ilmu hakikat hingga ma’rifat. Tauhid dan tasawuf menjadi nafas dalam semangat ngajinya.
“Nangiso le, nangiso nduk, nangiso wahai kanak-kanakku… tangisono doso-dosone bapak ibukmu, ndlosor lek perlu, sampean jalukno ngapuro maring Gusti Allah”, demikian dhawuh teduh mbah kakung di podium itu dengan suara terisak-isak.
Suara itu terus terngiang, hingga kanak-kanak tak kuasa meneteskan air mata sucinya. Namun satu hal yang membuatku heran terkagum-kagum. Kanak-kanak yang masih lugu dan polos itu bisa dibuat nangis sesenggukan, bukan karena kesakitan atau merasa diancam, namun karena merasa hatinya tersambung dengan Allah dan Rasulullah. Luar biasa. Sungguh ini masalah hati dan spiritual.
“Bagaimana keadaan batinmu, bagaimana keadaan hatimu, dan sejauh mana sinyal hatimu tersambung dengan sumber cintanya Allah, maka di situlah pesan spiritual dari omonganmu akan merasuk dalam hati lawan bicaramu”, begitu yang beliau dhawuhkan dalam setiap pengajiannya.
Ini tantangan untukku. Dilahirkan dari keturunan hamba Allah yang luar biasa ini. Merasa tidak pantas, minder dan seterusnya mungkin itu suatu kewajaran. Jikalau ayahku dipanggil “gus”, okelah mungkin tepat kiranya. Namun aku sangat malu mengaku-aku sebagai cucu kakekku.
Namun itu juga menjadi bentuk kasih sayang Tuhan yang perlu terlebih dulu aku terjemahkan hingga aku bisa meneguk air segar kasih sayang Tuhan melalui segala petuah dan quote-quote kakek yang selalu muncul hal baru di setiap pengajiannya. Sayang, saat itu usiaku yang membuat belum bisa menempatkan keseriusan yang pas untuk merekap setiap petuah beliau. Jadi jika seharusnya aku bisa mendapatkan 1000, namun karena naluri kekanak-kanakanku, maka aku hanya bisa mendapatkan 10 pun sangat ngoyo. Tapi tak apalah, aku yakin yang aku sadari hanyalah 10, namun yang dengan sendiri masuk dalam telingaku ada 990 sisanya, yang mungkin akan diproses suatu saat kelak saat keadaan hidup mengijinkanku mengaksesnya.
Namun ada satu kekaguman yang lain yang menghembuskan seamangat tersendiri mengenai perjuangan dan kehidupan. Jika engkau perhatikan saat Simbah kakung turun dari podium ia terlihat dengan posisi duduk di kursi roda. Iya benar, beliau lumpuh karena suatu penyakit yang masuk dalam tubuh beliau ingin mengirimkan pesan cinta dari Tuhannya. Jika di ndalem, beliau hanya bisa berbaring di ranjang juangnya. Begitulah beliau menamai amben berkasurnya yang biasa beliau tempati untuk tidur dengan sebutan “ranjang juang”. Ya karena memang itulah tempat beliau berjuang. Di setiap sabtu malam ahad, di ranjang itulah beliau ngaos, memberikan pengajian kepada masyarakat di sekitar desa, bahkan dari luar desa, ada juga yang dari luar kota, luar provinsi dan beberapa luar pulau. Walau rumahnya di mbale tidak muat, ada yang duduk di luar, ada yang duduk di serambi masjid,dan juga ada yang tetap duduk di atas sepeda motornya, bahkan ndodok atau jongkok di tanah halaman rumah.
“Hidup memang benar adalah buku pelajaran yang terbentang sepanjang usia”, tiba-tiba kata-kata bijak itu muncul dari mulut Kang Sadimin. Aku yang masih kanak-kanak dengan tertegun memandang wajah Kang Sadimin. Aku berada di tengah-tengah antara Kang Sadimin dan Cak Rodi. Mereka berdua sudah lama sekali ikut ngaji Mbah Kakung walaupun orang jauh, bukan asli Tulungagung.
“Iya….”. Sambil menatap ke atas langit merenungi isi pengajian Mbah Kakung Cak Rodi melamun.
“Heh Cak, Sampean itu bagaimana sih, diajak ngobrol kok malah ngelamun. Sampean apa kangen simbokmu di Demak?”, tukas Kang Sadimin sambil nyablek bahu Cak Rodi.
“Ora ngono lo min. Kalau kangen ya pasti to. Aku kok jadi mikir.”
“Mikir opo lo cak?”
“Tulungagung dulu adalah rawa-rawa. Sebutan itu disematkan bukan tanpa alasan. Konon Kota ini dulu sering banjir. Hingga bertransformasi, dilakukan berbagai perbaikan seiring berkembangnya pembangunan, jadilah Kota ini seperti sekarang yang bahkan kita tidur tidak ditakutkan soal banjir yang datang tiba-tiba”.
“Lha kenapa kok jok banjir cak”
“Sek to menengo. Belum selesai ngomong aku itu. Kamu nyela-nyela saja. Dadi ngene min. Setiap yang ada di bumi mengalami perubahan, pertumbuhan atau bahkan perkembangan. Artinya kehidupan terus berputar keadaan dan kondisi terus berubah. Lalu kenapa kondisi kedekatan kita dengan Gusti Allah kok tetep gini-gini saja. Bukannya segala kedinamisan hidup itu untuk bahan kita berfikir agar lebih ma’rifat padaNya?”
“Joh, mangkleke, sampean kok iso ujug-ujug bijak kayak gini piye to kang, hahahaha…..”.
“Sampean berdua itu ngomongin apa sih kang?”, sahutku dengan ketidak-mengertian.
“Hasil renungan dari yang disampaikan oleh Kakunge sampean barusan”, Cak Rodi menatapku dalam-dalam.
“Rame wae iki. Umek. Pengajiannya lo belum selesai”, sahut Mbah Juri dengan nada khasnya yang gontok. Sejenis seperti membentak dengan nada marah, tetapi sebenarnya tidak. Memang karakter ngomongnya seperti itu.
“Lha iyo to Mbah, Cak Rodi malah ceramah dewe. Kok enggak didengarkan dulu itu pengajiannya Yai Sulaiman sampai selesai dulu, baru nanti ceramah sendirian di kamar”, ejek Kang Sadimin sambil tertawa.
“Kowe iku yo menengo min. Fokus dengarkan pengajian dulu”, bentak Mbah Juri.
Kelihatannya dalam benak Cak Rodi sedang memikirkan hubungan alam dengan manusia. Seperti yang sering didhawuhkan oleh para orang tua, sesepuh pemegang erat kebudayaan Jawa, para Ulama’, bahkan Mbah Kakung juga tidak jarang selalu melontarkan pitutur itu.
Memang demikian adanya. Bahkan orang Jawa menganggap, memperlakukan dan memposisikan alam seperti sosok manusia. Mereka menjadikan alam sebagai sahabat, bahkan sebagai saudara sesama makhluk Tuhan yang manusia Jawa sangat menghormatinya. Sedekah bumi, larungan dan tradisi ritual yang lain yang berkaitan dengan alam menunjukkan betapa erat hubungan manusia dengan alam.
Namun saat tidur pun Cak Rodi tetap tidak bisa melepaskan kelekatan pikirannya terhadap yang tersirat didhawuhkan oleh Simbah Sulaiman. Di saat semua kawan-kawannya yang tidur di gotakan, kamar kosong dekat ndalem Mbah Kakung telah tertidur pulas semua, namun Cak Rodi tetap saja melamun, ketap-ketip matanya.
Paginya saat para kang (sebutan untuk mereka yang nyantri lama ke Kyai) sedang nguras kolam. Ada yang memindahi ikannya, ada yang menyikat dinding-dinding kolamnya, namun juga ada yang tetap jongkok melamun memandangi langit. Siapa lagi kalau bukan Cak Rodi. Sepertinya mengenai alam dan manusia belum berpindah dari ruang fikirnya. Lalu Kang Kabul yang iseng pun sengaja menyiramkan air satu timba ke mukanya Cak Rodi.
“Gacekane… apa-apaan ini. Hoe. Kok aku sing disiram”, dengan nada marah sekaligus kaget, Cak Rodi berteriak.
Yang lainnya tidak berhenti tertawa terpingkal-pingkal.
“Heh Kang Kabul, sampean nanti kuwalat lo. Dia sedang bertafakkur, bertadabbur, bahkan ia sedang berdzikir lo. Kok bisa-bisanya sampean siram air”, kata Kang Sadimin setengah mengejek.
“Yo bene to min. Biar dia sadar bahwa dunia ini tidak cukup hanya sekedar dilamunin saja”, jawab Kang Kabul.
“Iya betul. Dunia itu kan artinya sekejap atau sementara. Kalau sudah tahu sekejap, lalu buat melamun saja, habis dong waktunya untuk melamun saja”, tambah Kang Roni.
“Repot wes repot musuh wong pinter-pinter iki”, balas Cak Rodi.
“Piye to kang. Sebenarnya ada apa, kok melamun saja dari habis pengajian Yai Sulaiman tadi malam?”, tanya Kang Roni sambil nyablek pundak Cak Rodi.
“Alam diletakkan di kandungan batin manusia sebagai representasi kehadiran Tuhan. Ibarat hubungan anak dan ibunya, maka alam adalah ibu kita, dan kita sebagai anaknya”, sambil menatap ke depan dan berpaling dari teman-temannya. Wuiiihh. Sangat mirip adegan drama yang mengagumkan.
Lalu semuanya bengong, domblong, tertegun dan matanya menatap dalam-dalam ke Cak Rodi. Lalu tak lama kemudian terdengar suara serentak tertawa terbahak-bahak menertawai apa yang dikatakan Cak Rodi.
“Kalian itu bagaimana sih. Kan memang benar yang saya omongkan barusan”, membalikkan badan dan menatap kawan-kawannya.
“Gini kang, karena sampean itu tidak biasanya seperti ini. Kesambet demit mana sampean?”, tukas Kang Sadimin sambil tak bisa menahan tawanya.
“Bukannya seseorang itu jika mau mencari kebenaran atau ilmu hakikat harus diawali dengan perenungan yang mendalam yang diawali dari kegelisahan”, jawab Cak Rodi sok bijaksana.
Namun kayaknya kali ini para kang-kang yang lain mulai menanggapi dengan serius. Mulai ikut merenung apa yang dikatakan oleh Cak Rodi. Namun tiba-tiba terbuyarkan oleh suara panggilan Mbok Ginah, tukang adang nasi dan tukang masak yang membantu nenek di urusan dapur.
“Woy… Kang-kang, sompile wes ngawe-ngawe nek meja makan”, teriak Mbok Ginah.
Sompil merupakan makanan khas Tulungagung yang terdiri dari lontong, sayur lodeh dengan kekhasannya ada lotho (sejenis kacang), lalu tidak lupa ditaburi bubuk kedelai. Sangat mantab dan nikmat rasanya.
“Iyo mbok, asiyaaapp… Gasskan Cak. Ojok panggah mikir ngendeng ae”, sambil menepuk pundak Cak Rodi, Kang Sadimin meneriakinya.
“Ayo-ayo gassskan”, teriak sorai dengan penuh kegembiraan para Kang-kang yang telah selesai menyelesaikan pekerjaan hariannya.
Siangnya setelah selesai sholat dhuhur dan aktivitas mujahadahnya, Cak Rodi yang duduk-duduk di serambi masjid dihampiri oleh Gus Soleh. Kebetulan ada undangan untuk mengisi pengajian di salah satu desa di Tulungagung yang terletak di wilayah pegunungan, tepatnya di Kecamatan Pucanglaban.
“Cak… ayo ikut aku nek gunung”, ajak Gus Soleh
“Loh wonten nopo gus kok ke gunung?”, tanya Cak Rodi penasaran.
“Ngaji cak. Nek Kaligentong. Naiknya ya lumayan lah. Tapi adanya sepedah motor Cak. Bagaimana siap ya?”, Gus Soleh menjelaskan.
“Siap gus. Monggo pun”, kata Cak Rodi sambil bergegas mengambil sandalnya lalu menuju tempat di mana sepedah motornya di parkir.
Sepanjang perjalanan saat mengendarai sepedah motor, Cak Rodi sama sekali belum bisa melepaskan fikirannya dari masalah alam dan manusia. Sampai-sampai saat diajak ngobrol oleh Gus Soleh, ia sering tidak merespon karena tidak fokus, hingga dicablek pundaknya oleh Gus Soleh.
“Woy kang. Kalau nyetir itu jangan sambil nglamun”, kata Gus Soleh.
“Oh nggeh gus ngapunten. Saya tidak nglamun kok gus”, jawab Cak Rodi.
“Lha itu tadi saya ajak ngomong kok tidak ada jawaban”
“Maaf gus, mungkin tidak kedengeran karena memakai helm”
“Halah alasan kamu. Lha buktinya ini kok bisa dengar. Ada apa to sebenarnya apa yang kamu fikirkan?. Aku tadi sempat diceritani Kang Sadimin lo”
“Niku lo gus. Coba jenengan lihat di kanan-kiri kita. Kok keadaan hutan sudah seperti itu ya?. Banyak sekali pohon-pohon ditebangi tanpa ditanami kembali. Nebangnya pun juga tanpa dipilihi yang layak dan waktunya ditebang gus”
“lha terus cak?”
“lha nggeh niku gus. Sesuai yang disampaikan Yai Sulaiman kemaren mengenai hubungan manusia dengan alam. Jika kita tidak menjaga dengan baik hubungan kita dengan alam, maka bakal ciloko”
“Iyo bener cak”
Nampaknya memang Gus Soleh menyadari bahwa tatkala kebenaran yang disampaikan menghujam di dalam hati, maka saat itu juga kebenaran itu mulai berproses dalam fikiran hingga terimplementasi di dalam perilakunya. Kayaknya dalam benak Gus Soleh ia memprediksi bakal ada banyak kejutan yang akan terjadi dari dalam diri Cak Rodi.
Sesampainya di tempat pengajian, Gus Soleh pun langsung duduk di kursi VIP yang disediakan oleh panitia. Namun Cak Rodi memohon ijin untuk tidak ikut masuk di tarub pengajian. Ia ingin sebentar saja berjalan-jalan menikmati keindahan alam pegunungan sambil merefresh otaknya.
“Dalem ijin gus nggeh, tidak ikut masuk ke arena pengajian. Saya ingin jalan-jalan di sekitar sini dulu, merenungi banyak hal yang berjubel masuk dalam fikiran saya.”
“Okelah Cak, santai saja. Saya masuk duluan ya”
Cak Rodi pun menyusuri alam yang terbentang persawahan, tak sedikit juga pepohonan rindang menambah kesejukan dan hijau alam sekitar desa itu. Saat di tengah persawahan ia turun ke bawah, ia bertemu dengan kakek-kakek tua yang memakai capil, dengan memondong sak berisi rumput.
“Monggo mbah, baru dari mana?”
“Oh nggeh mas. Ini loh mas baru saja cari rumput untuk makanan lembu”
Namun dari arah yang berlawanan muncul bocah laki-laki dengan membawa celurit atau sabit atau arit.
“Kayu itu lebih tahan lama jika dibakar di pawonan mbah”, sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah pohon mahoni berumur dua tahunan. Sepertinya terbersit ide dalam benak bocah itu untuk menebangnya.
“Bocah gendheng. Kok dapuranmu koyok wong kutho sing gag duweni coro. Apa dipikir hidup itu cuma kanggo dewe’e tok. Opo podo ora mikir anak puthune”, jawab kakek itu dengan nada marah.
Bocah laki-laki itu tambak sedih, raut mukanya menggambarkan penyesalan telah mengundang amarah kakeknya. Lengking kemarahannya lebih kuat dari pada suara burung hutan. Ia semakin sering menyumpahi para orang kota, pegawai dan pengusaha yang tidak tahu diri mau menggunduli hutan untuk membuka lahan perkebunan. Bahkan tak sedikit ditebangnya pohon-pohon untuk keperluan bisnis mebel pribadinya.
Lalu kemudian bocah laki-laki itu pun kembali pulang dengan membawakan rumput yang telah berhasil ia kumpulkan dengan kakeknya.
Si kakek yang masih di situ untuk beristirahat sejenak tiba-tiba mengajak Cak Rodi jagongan (ngobrol santai) sambil duduk-duduk santai di rerumputan.
“Mriki lo mas pinarak. Jenengan saking pundi?”
“Oh kulo saking Tanjungsari mbah. Ini tadi mengantarkan Guse mengisi pengajian”
“Oh begitu ya mas”
“Ngapunten mbah. Memang di sini sering ya terjadi penggundulan hutan atau penebangan pohon secara sembarangan?”
“Woh enggeh mas. Sering mas. Itu mereka para orang kaya dari kota. Katanya mau membuka perkebunan lah, atau buat mebel lah. Padahal saat saya ketemu mereka sering sekali saya uneni, uring-uring”, Dengan ekspresi jengkel sambil menunjuk-nunjuk jarinya ke depan seakan-akan mempraktekkan sedang memarahi mereka yang menebang pohon sembarangan.
“Ojo dibabat kuwi, ojo ditebang iku, mengko Tulungagung dadi kidung”, dengan teriakan dan bentakan yang mungkin sudah lama dipendam simbah. Memang benar kata cucunya. Teriakan amarahnya melebihi suara burung hutan.
Singkat cerita Gus Soleh pun sudah selesai pengajiannya dan menelfun Cak Rodi. Maka berpulanglah mereka untuk turun gunung kembali ke Tanjungsari. Sepanjang perjalanannya pun Cak Rodi tidak berhenti memikirkan kejadian-kejadian yang diceritakan kakek yang ia jumpai saat jalan-jalan di alam. Tampaknya ia sedang menyusun rencana untuk berbuat sesuatu sekedar berbuat sebisanya untuk menunaikan apa yang menjadi konsep kebenaran baru di dalam hatinya mengenai alam dan manusia. Bahwa alam dan manusia adalah bersahabat. Maka hubungannya pun sangat perlu dijaga dan dipastikan terus baik-baik saja.
Ia pun mulai menjalin relasi dengan Dinas Perhutani. Hingga punya nomer telepon perangkat desa, para aktivis lingkungan. Bahkan akhir-akhir ini sering mendatangi diskusi-diskusi para aktivis lingkungan. Tak jarang juga mengikuti acara-acara penanaman sejuta pohon.
Bahkan di satu waktu, Cak Rodi mengajakku untuk mengumpulkan teman-temanku guna mengadakan kegiatan bersama berkenaan dengan misinya mengenai peduli lingkungan. Ia ingin mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam serta aksi nyatanya dalam ikut memeriahkan kegiatan penanaman sejuta pohon.
Bahkan ia pun juga ngadep sowan kepada kakekku meminta wirid untuk melancarkan segala usahanya dalam menyemaikan kebermanfaatan dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Ia setiap sore ba’da ashar dan sambil menunggu waktu maghrib tiba selalu duduk bersila dan fokus mengamalkan wirid yang ia dapatkan dari Mbah Yai Sulaiman.
Memang benar orang Jawa mencerdasi kehidupan dengan membangun hubungan baik dengan alam. Sahabat itu adalah alam. Sahabat manusia yang tidak bisa diganggu-gugat hubungan baiknya. Manusia sesungguhnya sangat tergantung kepada faktor alam. Paradigma orang Jawa terhadap alam merupakan sebuah capaian transformasi tertentu dalam menjalani spiritualitas. Alam adalah sahabat manusia. Perjuangan Mbah Kakung melalui ranjang juangnya telah membuka cakrawala berfikir santrinya. Tentunya itu semua adalah kuasa Allah. Laa Haula wa Laa Quwwata Illa Billah. Semoga bermanfaat. Wallahu A’lam Bish Shawwab.
Oleh: Agus Novel Mukholis