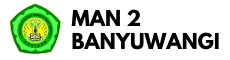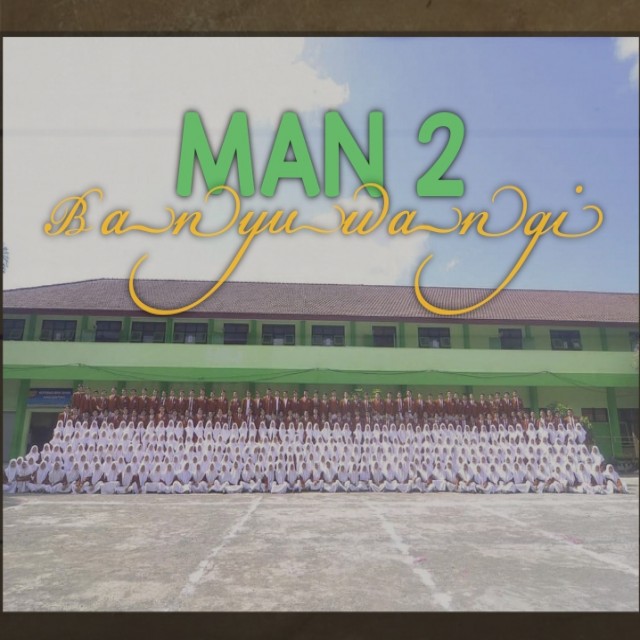Itulah mengapa wahyu yang pertama kali diterima Rasulullah Saw adalah perintah membaca atau iqra’. Tidak hanya membaca yang termaktub dalam Kitab Suci Al Qur’an, namun lebih dari itu membaca diri, membaca alam, membaca kehidupan, membaca fenomena, membaca apapun sisi dari kehidupan demi menemukan satu makna dan satu konsep untuk menentukan sikap hidup. Maka siapa saja yang melewatkan fase membaca, akan mengalami kebingungan yang hakiki, akan mudah terombang-ambingkan oleh kehidupan dan ketidak-pastian.
Sengaja menggoreskan pena pemikiran tentang membaca ini, ingin aku tujukan kepada para adek-adekku, anak-anakku, sahabatku dalam perjuangan yang mulai menelan mentah-mentah pola pemikiran, mind-set, pandangan hidup dari kebanyakan orang yang belum pernah melakukan pembacaan ulang atas kebenaran wacananya. Bahkan dijaga turun-temurun, seperti tradisi adat-istiadat, sehingga yang mencoba untuk melakukan pembacaan ulang dianggap salah bahkan gila.
Contoh dalam keseharian adalah mind-set yang tertanam di masyarakat jika seorang sarjana itu berbanding lurus dengan pekerjaan di perkantoran, pemerintahan, perusahaan ternama, bahkan PNS. Maka masyarakat akan memandang sebelah mata kepada mereka para sarjana yang memilih untuk berwirausaha, berjualan, berbisnis, turun ke sawah bercocok tanam atau pekerjaan apapun yang dianggap rendah.
Contoh yang paling kompleks adalah bagaimana seorang Tokoh Muslim yang sangat brilliant pemikirannya dalam menyegarkan kembali (refreshing) pandangan dan pengejawantahan terhadap Islam. Namun justru malah dianggap gila. Beliau adalah Nurcholis Madjid atau akrab disapa Cak Nur. Namun kita tidak akan membahas tentang pemikiran beliau dan pembaruan-pembaruan beliau, dalam sudut pandang terhadap pengejawantahan ajaran Islam dalam kehidupan. Mungkin di lain kesempatan dan di lain tulisan.
Yang akan kita bahas adalah bagaimana hubungan relasional antara pendidikan dan pekerjaan. Karena mayoritas masyarakat berpandangan dan bahkan melekat kuat dalam tradisi bahwa pendidikan (lebih tepatnya ijazah/bukti telah lulus) sangat menentukan pekerjaan dan bahkan kemapanan di masa depan. Masih beranggapan bahwa lembaga pendidikan adalah pabrik yang memproduksi tenaga-tenaga kerja industrialis.
Karena para generasi muda yang mulai menentukan pendidikannya di ranah perguruan tinggi atau universitas, mulai merasakan kebingungan dan kegundahan yang sumbernya adalah mind-set bahwa jurusan perkuliahan berbanding lurus dengan pekerjaan setelah lulus. Padahal tidak selalu seperti itu. Juga bukan berarti tidak benar. Ada sebagian yang berbanding lurus, namun juga tidak sedikit yang keluar jalur dari jurusan kuliahnya.
Namun bukan itu yang mengganggu. Masalahnya jika pandangan seperti itu sampai membuat kita menghapus kecintaan terhadap keilmuan, itu yang repot. Awalnya kita sangat mencintai keilmuan psikologi. Lalu sangat tertarik untuk mempelajari dan mendalaminya dengan kuliah ambil jurusan psikologi. Namun karena termakan dengan pandangan sebagian orang dengan analisa ngawur kalau jurusan psikologi kurang prospektif di masa depan, maka ia pun memupuskan keinginannya untuk memperdalami ilmu yang berhasil ia cintai. Ini kan sangat mengganggu kemurnian niat, kesungguhan tekad dan keterbangunnya cinta untuk menuntut ilmu. Padahal itu kunci dan hal paling penting dalam menuntut ilmu atau mempelajari sesuatu, yaitu menimbulkan cinta atas kelimuan.
Karena termakan oleh pandangan tersebut tidak sedikit yang membelokkan haluan dengan memilih jurusan-jurusan di perkuliahan yang dipandang aman dalam menjamin keterdapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan setelah lulus kuliah. Hal ini yang hulunya akan terjadi penumpukan mahasiswa hingga overload. Jika semua generasi berfikir bahwa jurusan, fakultas, universitas bahkan negara bisa menyediakan pekerjaan untuk mereka tatkala telah lulus, maka yang terjadi adalah bertumbuhnya ribuan generasi dengan mental “berpangku tangan”. Hulunya akan banyak yang berfikiran jika kuliah di jurusan Pendidikan Agama Islam dengan kapasitas kelulusan seribu Sarjana Pendidikan Islam per-tahun, maka per tahun pun negara dan pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan sebagai Guru Pendidikan Agama Islam dengan jumlah yang sama yaitu seribu kursi. Namun faktanya kan tidak demikian. Kata kuncinya kan, “Lembaga Pendidikan bukan Pabrik Industrialisasi, bukan penghasil tenaga kerja, bukan tempat pelatihan kerja”.
Ditambah lagi jika para generasi muda masih menggantungkan cita-citanya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan para orang tua masih terobsesi anaknya menjadi PNS, maka akan bermunculan ribuan sarjana tiap tahun menunggu dibukanya recruitment PNS. Padahal faktanya tidak setiap tahun ada. Kalaupun ada tidak mungkin menyediakan kursi sejumlah sarjana yang lulus tiap tahunnya. Bahkan di beberapa kesempatan, aku sering mengatakan kepada generasi muda bahwa di masa depanmu bukan saatnya lagi untuk bercita-cita menjadi PNS. Namun sudah saatnya untuk bercita-cita dan mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha muda yang sukses. Bisa dibayangkan semua generasi muda mempunyai impian untuk menjadi pengusaha muda yang sukses, maka akan semakin banyak tercipta lapangan pekerjaan di masa depan.
Maka pembacaan ulangnya adalah bagaimana memulai diri memunculkan kecintaan terhadap keilmuan lalu berfokus terhadap pendalamannya. Jadi saat “kuliah” atau “belajar” jangan sekali-sekali memikirkan besok kerjanya jadi apa saat lulus. Itu sangat meterialis dan mengganggu kemurnian cintamu atas kelimuan. Fokus pada kewajiban kita untuk terus belajar diniati ibadah, mengabdikan diri kepada Allah, maka pekerjaan dan penghidupan akan ditata oleh Yang Maha memberi rizki. Ironinya lembaga pendidikan sangat piawai mengajarkan kita tentang penghidupan (bagaimana menjalani keprofesian sehingga mendapatkan upah atau gaji), namun sangat jarang yang bisa mengajarkan tentang kehidupan. Padahal pemahaman tentang kehidupan adalah modal untuk survive dalam segala kondisi kehidupan.
Yang terpenting meningkatkan kualitas diri tentang pengetahuan, skill dan keilmuan. Maka yang terjadi selanjutnya adalah pekerjaan yang akan menghampiri para ahli, para pakar dan mereka yang berpotensi dan berkompeten. Kalaupun toh pekerjaan yang digeluti setelah lulus tidak ada kaitannya dengan jurusan di perkuliahan, itu pun tidak jadi soal. Toh juga banyak dan di Indonesia lah tempatnya orang-orang dengan keahlian di beberapa bidang namun setengah-setengah semuanya. Tidak ada yang benar-benar ahli.
Yang berdosa itu adalah kegagalan untuk memasyarakatkan ke-sarjanaan kita. Masyarakat pada umumnya, minimal orang-orang di sekitar kita termasuk keluarga kita, jikalau sama sekali tidak mendapatkan kebermanfaatan dari kesarjanaan kita, maka itu yang dinamakan gagal sebagai “sarjana”. Jika antipati terhadap permasalahan sosial, maka itu juga definisi dari kegagalan sebagai sarjana.
Wa ma uutitum minal ‘ilmi illa qaliila (dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit). Maka itu pun juga harus menjadi landasan untuk tidak berhenti belajar dan melakukan pembacaan terhadap kehidupan. Karena menjadi sarjana bukan berarti menjadi orang di menara gading. Justru letak kesarjanaan adalah letak kesadaran akan tanggung-jawab sebagai pengabdi. Abdi atas Tuhannya, sekaligus abdi dan pelayan untuk kemanusiaan, untuk kebenaran serta untuk kedamaian. Hulunya pada penyemaian kebermanfaatan, rahmatan lil ‘alamin sebagai ruhnya agama.
Jika prinsip itu telah tersemai dalam hati serta terejawantah dalam karakter dan sikap, maka pembacaan ulang atas makna pekerjaan juga akan lebih murni dan cerah. Jika kita berfikir dan mencoba membaca ulang makna pekerjaan, selanjutnya bertanya-tanya sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pekerjaan itu. Bahkan Cak Nun dalam forum Maiyah dalam rangka sinau bareng pernah menggiring pemikiran jama’ah mengenai esensi dari pekerjaan. Memulainya dengan lontaran pertanyaan, “apakah menjadi seorang Bupati atau Gubernur itu pekerjaan ataukah pengabdian? Berdasarkan apakah sesuatu itu disebut pekerjaan? Apakah berdasarkan kaitannya dengan uang yang diperoleh dari pekerjaan tersebut? Jika iya, sulitlah kiranya seseorang yang menjabat sebagai bupati disebut, pekerjaan: bupati; dikarenakan tekanan utama jabatan bupati adalah pada pengabdiannya kepada masyarakat”.
Maka seketika term mengenai pekerjaan menjadi tidak fixed dan tidak stabil dalam pustaka fikiranku. Maka melalui ungkapan Cak Nun di atas, kita dapat meninjau ulang mengenai pekerjaan dan uang. Ini kemudian dipertegas oleh Mbah Nun di awal Sinau Bareng dengan mengatakan bahwa sebenarnya dalam setiap pekerjaan itu ada makna ganda. Yaitu, suatu pekerjaan dilakukan sebagai jalan untuk mencari uang/nafkah, tetapi juga sekaligus sebagai jalan untuk nyenengke/ngabekti kepada Allah. Maka itu semua ada kaitannya dengan manusia nilai, manusia pasar dan manusia istana. Pembagian manusia dalam tiga dimensi itu masih dalam pembahasan Cak Nun mengenai pekerjaan, manusia dan uang. Semoga di kesempatan dan tulisan lain bisa membahas terkait tiga dimensi manusia tersebut. Jelasnya bahwa uang adalah akibat, uang adalah tanda syukur, dan uang adalah buah dari ketulusan kita dan kesetiaan kita dalam menjalani pekerjaan dengan niat mengabdi kepada kemanusiaan, kebenaran, keluhuran, kemuliaan dan puncaknya pengabdian kita kepada Tuhan.
Oleh : Agus Novel Mukholis, S.Psi.I